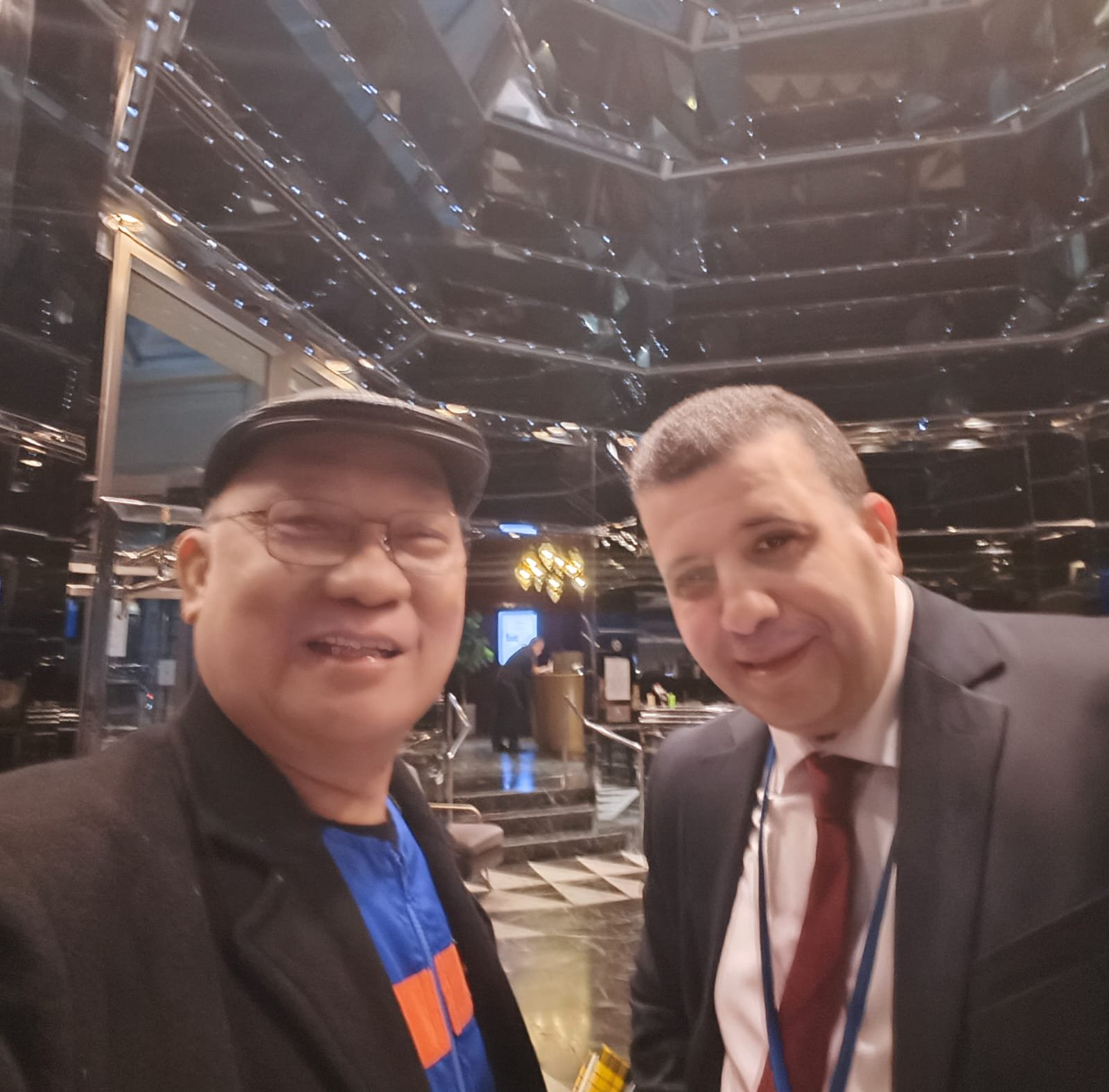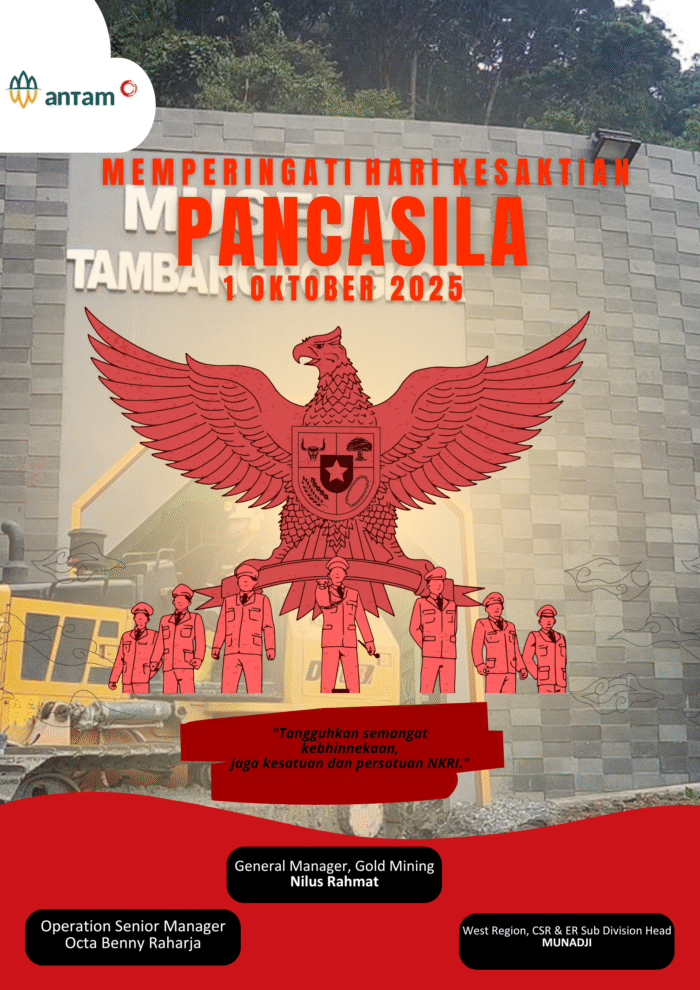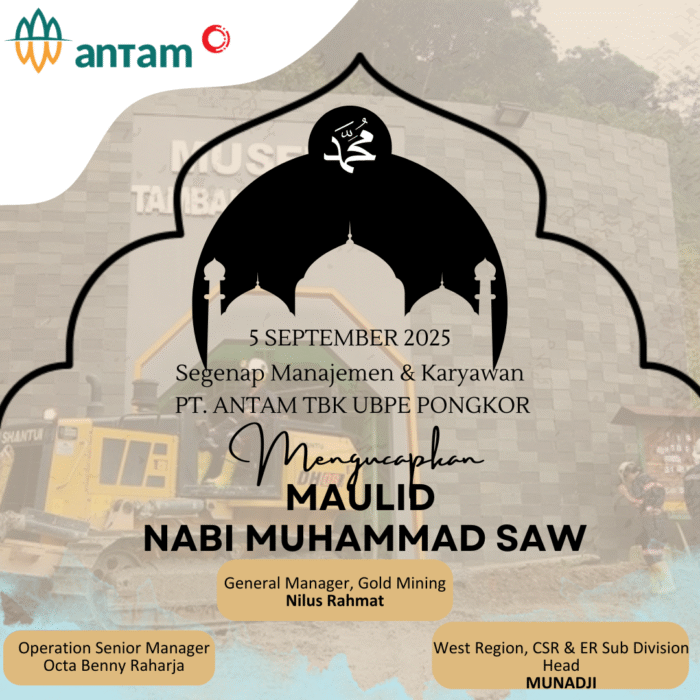Liputan08.com – Setiap 2 Mei, kita kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan penuh seremoni: pidato pejabat, upacara bendera, dan parade kutipan Ki Hadjar Dewantara. Namun di balik panggung simbolik itu, dunia pendidikan Indonesia tengah mengalami luka struktural yang nyaris tak terdengar: profesi guru yang semakin kehilangan daya hidupnya.
Fenomena guru yang harus bekerja sambilan demi memenuhi kebutuhan dasar bukanlah cerita baru. Dari menjadi pengemudi ojek daring, penjual online, hingga buruh lepas, mereka menjalani profesi ganda bukan karena kurangnya dedikasi, melainkan karena negara belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang layak. Ironisnya, guru kerap ditempatkan di altar penghormatan moral dalam pidato-pidato publik, tetapi diabaikan dalam kebijakan struktural yang menjamin kehidupan yang bermartabat.
Di saat yang sama, ribuan lulusan fakultas pendidikan memilih untuk “switch career” ke sektor lain—mulai dari perbankan, industri kreatif, hingga bidang teknologi. Fenomena ini bukan soal kegagalan idealisme, melainkan respons rasional terhadap ekosistem pendidikan yang minim insentif profesional. Jika menjadi guru justru memperbesar ketidakpastian ekonomi, bagaimana bisa kita berharap profesi ini tetap diminati?
Kritik tajam terhadap kondisi ini pernah dilontarkan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970). Ia menyebut bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menindas. Namun bagaimana mungkin guru bisa membebaskan peserta didik jika ia sendiri tidak dibebaskan dari belenggu struktural dan tekanan hidup? Bagaimana mungkin mengajarkan berpikir kritis jika waktu dan pikirannya habis untuk bertahan hidup?
Tidak hanya itu, sistem birokrasi pendidikan kita yang rigid justru mempersempit ruang inovasi guru. Kurikulum yang terus berubah, beban administrasi yang berlebihan, serta indikator keberhasilan yang terlalu teknokratis membuat guru tidak lebih dari pelaksana kebijakan dari atas—bukan pendidik yang otonom dan reflektif.
John Dewey pernah mengingatkan, “A society which neglects education, or gives it a secondary place, is destined to be stagnant and backward.” Tapi kita sering lupa bahwa pendidikan bukan sekadar bangunan sekolah atau kurikulum, melainkan manusia yang menghidupkannya—guru.
Maka Hari Pendidikan Nasional bukan hanya waktu untuk mengingat jasa para pendidik, melainkan momen untuk menggugat. Menggugat sistem yang membuat guru tak berkembang. Menggugat negara yang hanya memberi ruang pujian, tapi bukan keberpihakan. Dan menggugat budaya pendidikan yang lebih sibuk menata angka ketimbang menyentuh makna.
Tanpa keberanian untuk mengubah akar struktural yang timpang, pendidikan akan terus berjalan di atas luka, dan Hari Pendidikan Nasional hanya menjadi seremoni yang tak pernah menyentuh realita.
Oleh: Ardian Fatkhurohman, S.Pd
Baca Juga
-
20 Mar 2025
KH Achmad Yaudin Sogir Sampaikan Tausiah di Diskominfo Kabupaten Bogor Jutaan Pahala di Bulan Ramadhan
-
31 Jan 2025
Heboh! Ular Jenis Kopi Ditemukan di Kantor Labkesda Cimanggis Depok
-
09 Apr 2025
KEJAGUNG SITA RUMAH MEWAH MILIK TONY BUDIMAN TERKAIT KASUS PAJAK SENILAI RP634 MILIAR
-
21 Mei 2025
Bupati dan Wabup Bogor Komit Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK Apresiasi Lonjakan Skor MCP
-
26 Jul 2025
Jumling di Jonggol, Wabup Jaro Ade Sampaikan Arahan Bupati Bogor dan Serap Aspirasi Warga Singajaya
-
17 Des 2024
Rutan Kelas IIB Rengat Gelar Razia Blok Hunian, Tegaskan Komitmen Zero Halinar
Rekomendasi lainnya
-
28 Jul 2025
Dukung Arahan Rudy Susmanto, Dishub Bogor Tingkatkan Perawatan Lampu Jalan untuk Ciptakan Wilayah Aman dan Nyaman
-
26 Jan 2025
Pj. Bupati Bogor Perkuat Ukhuwah Islamiah Melalui Shalat Subuh Keliling di Parung
-
10 Jan 2025
Pengurus Baru LASQI Kabupaten Bogor Resmi Dilantik, Dorong Seni Qasidah Jadi Ikon Budaya Islam
-
05 Nov 2024
Pemkab Bogor Gelar Festival Catur Pelajar 2024, Dorong Minat dan Bakat Generasi Muda dalam Olahraga Catur
-
21 Apr 2025
Pemkab Bogor Tindak Tegas Perusahaan Pencemar Setu Rawa Jejed, DLH Segel dan Tutup Saluran Pembuangan Ilegal
-
22 Apr 2025
Dua Saksi Kunci Kasus Jiwasraya Koruptor Makin Tak Nyaman Bukti Kian Menguat!